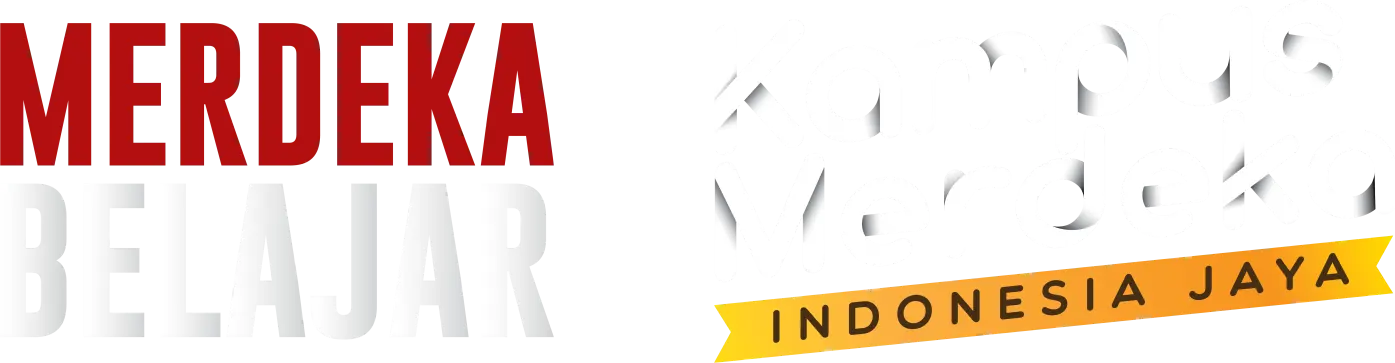‘Political Will’ Selamatkan Hutan, Presiden Harus ‘Back-Up’ Penuh Menhut
Menguatnya faktor penyebab terjadinya dua bencana alam ekologis yang menelan korban jiwa besar di awal tahun 2006, yakni banjir bandang dan tanah longsor di Jember, Jawa Timur, dan tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah adalah karena rusaknya kawasan hutan, dinilai seorang ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bahwa aksi menyelamatkan hutan benar-benar harus dijadikan hal yang fundamental para pihak yang berkaitan.
“Dalam kaitan ini, ‘political will’ aksi penyelamatan hutan di Indonesia yang rusak memerlukan ‘back-up’ penuh Presiden, karena secara horizontal seringkali langkah-langkah Menteri Kehutanan (Menhut) mendapat masalah di level horizontal,” kata Dr Ir Ricky Avenzora, MSc, staf pengajar Fakultas Kehutanan IPB di Bogor, Kamis.
Hal itu dikemukakannya saat diwawancarai Antara sehubungan dengan dua bencana alam ekologi yang sedang terjadi di Jember dan Banjarnegara itu. Ia mengemukakan, problem di level horizontal itu banyak terlihat dalam kasus-kasus “memerangi” salah satu tindakan yang paling banyak merusak kondisi hutan seperti pembalakan liar (illegal logging), dimana para pelakunya ketika diproses di jalur hukum (pengadilan) ternyata hanya mendapat hukuman ringan, dan malah tidak sedikit yang dibebaskan.
“Ini adalah contoh dimana ada problem horizontal dari komitmen kuat Menhut yang ingin memberantas penyebab kerusakan hutan, namun membuat frustasi karena kerja keras untuk itu kemudian kandas di luar wewenang bidang kehutanan,” katanya.
Dengan kondisi itulah, kata dia, dukungan penuh dari Presiden, seperti dengan terus-menerus mengontrol agar kesepakatan-kesepakatan di level antar institusi kementerian dan juga lembaga penegakan hukum agar berjalan, adalah wujud dari “political will” dimaksud.
“Dua kasus bencana terakhir yakni di Jember dan Banjarnegara mestinya sudah cukup untuk menyudahi tindakan tidak bertanggung jawab sedikit orang yang mengeruk keuntungan besar dari hutan, namun ketika alam rusak dan terjadi bencana, banyak korban jiwa jatuh,” katanya.
Di sisi lain, Ricky Avenzora juga menyatakan bahwa sinergi antara Dephut dengan kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat), khususnya yang berfokus pada lingkungan, termasuk soal-soal kehutanan, perlu terus dibangun, karena kalangan LSM cukup mempunyai data, terutama soal pemetaan kawasan-kawasan hutan kritis.
Ia melihat bahwa sinergi itu belum tertata dengan baik, dengan parameter masih tajamnya secara frontal antara LSM dengan Dephut sebagai otoritas kehutanan di Indonesia. “Sinergi itu bisa disebut optimal tatkala terjadi semacam konsensus untuk aksi bersama bagi upaya-upaya penyelamatan hutan dan tidak lagi frontal,” katanya.
Menurut dia, sebenarnya di kalangan LSM atau lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan, sudah mempunyai beberapa model institusional bagaimana membangun sinergi antara masyarakat di sekitar hutan, untuk tetap dapat memanfaatkan hutan pada area-area tertentu tanpa konflik.
“Tentu, model-model seperti itu, yang tetap mengedepankan kultur dan kearifan lokal bisa dikembangkan di kawasan-kawasan hutan di Indonesia, karena bagaimanapun juga masyarakat di sekitar hutan memang hidup dari hutan juga,” katanya.
Melihat dua bencana alam ekologis di Jember dan Banjarnegara itu, kembali ditegaskannya bahwa tingkat kritis hutan di Indonesia, termasuk hutan di Pulau Jawa yang jumlahnya semakin menurun, aksi yang bersifat segera bagi upaya-upaya penyelamatan, memerlukan “political will” yang amat kuat, dan saat ini membutuhkan dukungan penuh dari seorang Presiden RI.
Proses panjang
Sementara itu, pakar lingkungan IPB Prof Dr Ir Dedi Soedharma secara terpisah mengemukakan, terjadinya bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor di jember dan Banjarnegara itu sebagai sebuah proses panjang kerusakan lingkungan, yang unsur penyebab terjadinya tidak bisa dilihat hanya dalam waktu dekat ini.
“Bencana-bencana seperti di Jember dan Banjarnegara itu, adalah sebuah potret kerusakan lingkungan di Indonesia, yang prosesnya panjang sejak bertahun-tahun,” kata Direktur Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB itu. Menurut Dedi Soedharma, kerusakan lingkungan yang kemudian berimplikasi pada terjadinya bencana alam seperti di Jember dan Banjarnegara itu, tidak bisa terlepas dari konteks masa lalu mengenai pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kerusakan hutan.
“Saya sependapat dengan kalangan yang memaparkan bahwa kondisi hutan-hutan di Pulau Jawa saat ini benar-benar kritis, itu bisa dilihat dari jumlahnya yang kian mengecil, yang penyebabnya juga beragam,” katanya. Selain yang sudah sama-sama diketahui mengenai pembalakan liar (illegal logging), kata dia, masalah ikutan yang kemudian ikut memberi iuran bagi percepatan kerusakan alam dan lingkungan adalah karena ada sistem pertanian di sekitarnya yang tidak sesuai dengan konservasi air.
“Yang lebih parah, hutan lindung pun, yang seharusnya benar-benar dijaga dari penebangan malah dijarah, tentu kondisi-kondisi semacam ini mesti ditangani secara serius bila kita tidak ingin ada korban-korban manusia atas kerusakan alam itu,” katanya. Ditambahkannya bahwa di kawasa Selatan Jawa Barat (Jabar), sebuah suaka margasatwa pun menjadi sasaran penjarahan, sehingga bukan saja hutannya rusak, satwa liar yang dilindungi seperti banteng dan lainnya juga sudah terancam punah.
“Mestinya, dengan contoh-contoh terjadinya bencana seperti yang kini terjadi di Jember, Banjarnegara sudah cukup untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menghancurkan alam dan lingkungan hidup, yang akhirnya membawa korban manusia itu,” katanya. Sementara itu, menjawab pertanyaan mengenai munculnya dua kutub besar, khususnya saat terjadi bencana alam, dimana otoritas pemerintahan menyatakan tidak ada hutan yang rusak,sementara kalangan LSM dan pihak kritis lainnya mengungkapkan bencana itu akibat hutan yang rusak, ia menegaskan bahwa tak perlu lagi ada perdebatan wacana yang hanya melahirkan kontroversi saja.
“Otoritas pemerintahan absah saja melakukan pembelaan diri (bahwa tidak ada hutan rusak), tapi sebaiknya terjun saja langsung ke lapangan, lihat kondisi riil hutan yang ada,” katanya. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim menilai bahwa pernyataan Gubernur Jatim Imam Utomo soal penyebab musibah banjir bandang dan longsor di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember bukan akibat kondisi hutan yang gundul, menyesatkan dan membohongi publik.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Ridho Syaiful Ashadi menanggapi pernyataan gubernur soal musibah bencana alam di Jember.”Itu pernyataan yang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab. Tidak seharusnya gubernur sebagai pejabat publik mengambil kesimpulan begitu cepat,” katanya.
Gubernur Jatim Imam Utomo saat mendampingi Menko Kesra Ir Aburizal Bakrie meninjau lokasi bencana membantah anggapan bahwa banjir bandang yang menyebabkan puluhan nyawa melayang sebagai akibat dari gundulnya hutan di pegunungan Hyang Argopuro.”Hutannya utuh kok. Banjir itu, karena di atas ada cekungan yang berisi air dan selama ini tertahan oleh timbunan kayu-kayu tua dan kemudian ambrol,” katanya.
Menurut Dedi Soedharma, pada banyak kasus bencana di Indonesia debat klasik semacam itu selalu muncul, namun dengan referensi yang ada hendaknya tidak lagi dilakukan, namun mesti melakukan langkah tepat dan efektif, baik jangka pendek, menengah dan panjang. “Jangka pendekanya adalah menyelamatkan para korban bencana, dan menengah serta panjangnya adalah memperbaiki secara sistemik pembangunan berparadigma lingkungan, termasuk secara mendasar melakukan pemetaan secara serius pada hutan-hutan kritis di Pulau Jawa saat ini,” katanya. (ant/mim/rep/man*)