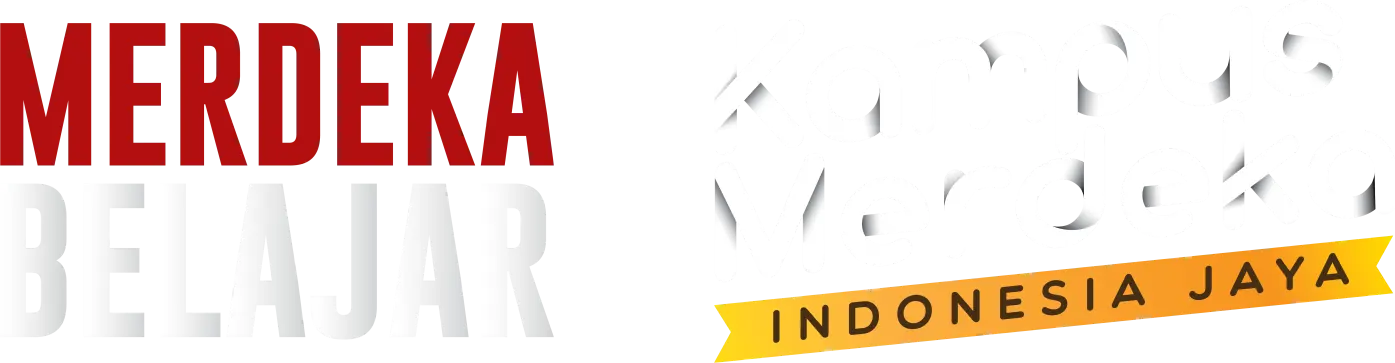Guru Besar IPB Tawarkan Strategi Pemanfaatan Satwa Liar Secara Optimal dan Berkelanjutan

Dalam skala dunia, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang mengagumkan: tertinggi untuk kupu-kupu (1.600 jenis), peringkat kedua dunia untuk mamalia (515 jenis) dan untuk reptilia (600 jenis), ke-5 untuk burung (1.531 jenis), dan peringkat ke-6 dunia untuk amfibia (270 jenis). Lebih dari itu, Indonesia memiliki 35 jenis primata (ranking ke-4 di dunia dimana 18 persen diantaranya endemik) dan sekitar 1.400 jenis ikan tawar.
Akan tetapi anehnya, kontribusi kekayaan satwa liar yang tinggi tersebut masih belum terasa secara nyata baik terhadap perekonomian nasional maupun dalam pemenuhan kebutuhan rakyat sekitarnya (terutama pemenuhan kebutuhan protein hewani). Padahal Undang-undang (UU) No. 5 tahun 1990 mengamanatkan bahwa sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.Dr. H. Yanto Santosa, ada dua permasalahan mendasar sehingga pemenuhan UU No. 5 Tahun 1990 tersebut ibarat “jauh panggang dari api”. Pertama adalah larangan melakukan kegiatan pemanenan satwa liar di kawasan konservasi, dan kedua adalah penetapan status jenis satwa dilindungi UU, status kelangkaan/kepunahan oleh CITES atau Red Book IUCN.
“Kajian terhadap kriteria yang digunakan dalam penetapan status populasi yang dilakukan oleh UU-RI, IUCN maupun CITES kurang jelas dan belum terukur. Selain itu, lebih aneh lagi status populasi yang ditetapkan berlaku bagi satu jenis satwa di seluruh nusantara,” ujarnya saat konferensi pers pra orasi di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor (22/9).
Padahal beberapa penelitian terhadap populasi monyet ekor panjang, rusa timor, orang utan, komodo, wallaby, owa, lutung dan banteng menunjukkan bahwa parameter demografi populasi satwa liar bersifat site-spesific. Dimana untuk jenis satwa yang sama belum tentu memiliki parameter demografi yang identik bilamana kondisi habitatnya berlainan. Oleh karena itu, maka proses penilaian dan penetapan status populasi seharusnya juga bersifat spesific-site (hanya berlaku untuk satu populasi saja).
“Penetapan status populasi untuk suatu jenis satwa yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh UU-RI, CITES dan IUCN perlu segera direvisi,” ujarnya.
Demikian pula halnya dengan larangan pemanenan satwa liar di kawasan konservasi yang lebih mendasarkan pada teori. Padahal kegiatan pemanenan sangat diperlukan dalam pengelolaan populasi satwa liar apapun status kawasannya. Pemanenan ditujukan untuk menyeimbangkan sex-ratio. Pada saat laju pertumbuhan populasi tinggi (terjadi ledakan/telah dianggap “hama”) oleh masyarakat sekitarnya sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat laju pertumbuhan populasi atau keseimbangan rantai makanan.
“Selain untuk manajemen populasi, pemanenan juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan potein hewani masyarakat lokal/sekitar, sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, sebagai wahana rekreasi berburu, dan untuk mengurangi konflik manusia-satwa,” ujarnya.
Maka strategi pemanfaatan satwa liar secara optimal dan berkelanjutan berupa: identifikasi/analisis manfaat optimal, revisi kriteria penetapan dan re-evaluasi status populasi, penetapan kebijakan pemanenan satwa liar di habitat alami, penentuan metoda penghitungan kuota panenan lestari dan penanganan zoonosis perlu segera direncanakan secara cermat dan komprehensif serta dilaksanakan secara sistematik, efektif dan efisien. “Dan senantiasa melibatkan masyarakat setempat dan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya. (zul)